Featured
- Get link
- X
- Other Apps
Cerpen: Boneka Ayah II
Halaman rumahnya kosong. Raras tidak melihat mobil hitam terparkir. Langkahnya ringan memasuki rumah. “Bi! Aku pulang.” Raras duduk di kursi tamu. Tubuhnya menunduk untuk melepaskan tali sepatu.
“Darimana kamu?” Tangannya berhenti melepaskan kaus kaki yang baru setengah terlepas. Dia ragu untuk menjawab. Suara itu tidak seharusnya yang pertama ia dengar. Suara lembut bibinya adalah hal yang paling ia rindukan saat pulang ke rumah, bukan suara berat lelaki itu. “Rumah teman, Pa.” jawab Raras singkat.
“Papamu lagi ngomong.” Kalimat singkat itu dan Raras langsung menegakkan tubuh di atas kursi. Wajahnya lurus ke depan, pandangannya mantap menatap satu titik di hadapannya. Bukan, bukan wajah papanya yang sedang duduk diseberang yang ia tatap. Pandangannya seakan menembus tengkorak kepala lelaki tua itu. Raras tidak akan pernah menatap mata papanya. Tidak diizinkan. “Orang berpangkat rendah harus menghormati atasannya.” Raras tidak perlu merapalnya lagi seperti mantra. Ia sudah menghafalnya seperti lagu pengantar tidur.
“Ke rumah siapa? Kamu nggak bilang.” Papahnya meneguk kopi hitam yang barusan disuguhkan bibi. Masih mengepul panas dan beraroma pahit.
“Ke rumah Lita. Papa bisa telepon kalau nggak percaya.” Bagai sudah diprogram, kata-katanya lancar terucap. Raras hanya ingin segera masuk ke kamar dan tidur.
“Bi, siapin makan malam.” Pria tua itu beranjak dari kursi menuju ke ruang makan. Raras baru bisa bernafas lega. Tubuh lelahnya ia seret ke lantai dua. Belum juga setengah tangga, suara itu kembali terdengar, “Setelah ganti baju, turun. Papa mau bicara.” Untuk kesekian kalinya, Raras mengutuk malam hari.
Tas yang hanya berisi satu buku tulis dan sebatang pulpen itu Raras lempar begitu saja ke lantai sesaat setelah memasuki kamar. Ia menjatuhkan tubuhnya di atas kasur yang empuk dan melenguh pelan. Matanya tanpa sadar terpejam, merasakan kenyamanan yang melingkupinya. Pikirannya melanglang buana, memutar kembali kejadian sepulang sekolah tadi. Sampai kapan ia akan hidup seperti ini? Sebentar lagi ia ujian lalu lulus dari SMA. Sebentar lagi ia harus menentukan mau seperti apa hidupnya ke depan. Menentukan? Raras hanya bisa tersenyum pahit.
Pintu diketuk pelan dari luar. “Non, bibi bawa jus alpukat. Diminum dulu.” Raras bergegas bangun dari kasur dan membuka pintu kemudian mempersilahkan Bi Sum masuk. “Makasih, Bi. Raras minum, ya.”
“Non, maaf tadi bibi nggak bagi tahu Non kalau bapak sudah pulang.”
“Santai aja, Bi. Ini juga salah aku karena pulang telat. Tapi kok mobil papa nggak ada di luar?”
“Tadi bapak diantar langsung dari markas. Kayaknya pakai mobil dari sana, bibi juga nggak paham.” Raras hanya mengangguk. “Oiya, sini gelasnya kalau sudah selesai. Bapak sudah nunggu di bawah.” Raras hampir saja lupa. Segera ia berganti baju dan turun ke lantai satu, menemui papanya yang sudah duduk di ruang keluarga.
Baru saja sampai, telinganya sudah disuguhi suara yang tidak mengenakan, “Papa kira ganti baju tidak sampai lima menit.”
“Maaf, tadi Raras ngecek PR dulu, Pa.”
“Duduk.” Kemudian Raras duduk di kursi seberang Papanya. Keduanya diam, tidak ada suara yang memulai untuk berbicara. Suasana malam itu dingin, sedingin ikatan ayah dan anak itu. Raras duduk dengan punggung tegap dan pandangan lurus, menunggu orang di seberangnya mengeluarkan suara. Haram bagi Raras untuk berbicara mendahului sang papa. Setelah sekali lagi menyesap cairan hitam di gelas besar itu, si pria tua mulai angkat suara.
“Besok kamu ke rumah Tantri. Urus kakakmu selagi kami bicara.” Nama yang terucap dari bibir pria itu seperti sebuah kutukan. Raras ingat betul tepatnya tiga bulan yang lalu, papanya menolak untuk memanggil wanita yang masih berstatus sebagai istrinya itu dengan panggilan kesayangan. Setelah pertengkaran hebat keduanya pada suatu malam yang berujung dengan minggatnya sang mamah ke rumah nenek dan kakeknya, membawa serta sumber pertengkaran yang saat ini entah Raras rindukan atau tidak, kakaknya, Mas Raga.
“Iya, Pa.” Raras muak berbasa-basi. Hatinya lelah menahan emosi yang dia sendiri tidak mengerti. Kesal, benci, marah, sedih, semua bercampur aduk saat ia ingat satu sosok itu.
“Selama kamu di sana, jangan pergi ke mana-mana. Fokus sama latihan kamu,” Jari Raras terkepal kuat, buku-buku jemarinya memutih tapi tersembunyi dengan baik di balik bantal sofa yang cukup besar di pangkuannya. “Nggak usah ikut Lita belajar buat ujian di kafe. Papa tahu yang terbaik buat kamu di masa depan.”
Lihat, Raras memang hanya bisa tersenyum pahit.
-Bersambung-
Popular Posts
Sistem Informasi : "Jangan samakan aku dengan sub-sistem!!"
- Get link
- X
- Other Apps
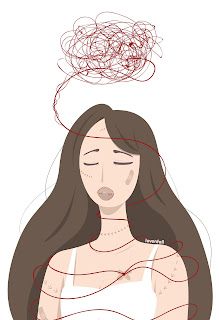

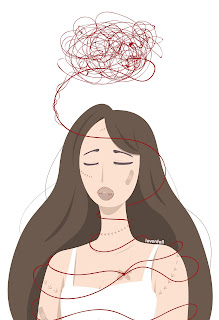
Comments
Post a Comment