Featured
- Get link
- X
- Other Apps
Cerpen: Boneka Ayah I
“Ras, hari Minggu besok ada acara nggak?” Lita berdiri di samping meja. Kedua tangannya nampak kesulitan mengatasi beban dua buah buku yang sedang ia dekap di dada, yang satu tipis berwarna kuning cerah dan satunya lagi tebal berwarna dominan hitam. Tebalnya bukan main, mengalahkan buku ensiklopedia kumbang kotoran yang dulu sering Raras baca.
“Kenapa memang?” Raras sudah selesai merapikan isi tasnya yang seringan bulu. Bersiap meninggalkan sekolah karena bel pelajaran terakhir sudah berbunyi lima belas menit yang lalu. Rencananya memang begitu, tetapi rasa-rasanya tidak jadi. Niatnya urung saat melihat sosok mungil sahabatnya mengintip dari luar jendela kelas barusan.
“Mau ngajak kamu belajar di kafe,” ucap Lita. Jari-jarinya mulai gemetaran dan ujung kukunya memutih. Raras tidak tahan, buku berdominan hitam itu dia ambil dari lengan kurus Lita. Sahabatnya sedikit terkejut, tetapi membiarkannya seolah itu memang tugas Raras.
“Kita ngomong sambil jalan ke depan ya. Aku mau ke warung.” Raras berjalan ke luar kelas mendahului Lita. Tubuh tinggi semampainnya dibalut seragam putih-abu dan jaket merah. Lita menyusul dengan langkah cepat. Kaki pendeknya sulit mengimbangi langkah lebar yang dibuat kaki jenjang milik Raras. Merasa sahabatnya tertinggal di belakang, Raras berhenti dan menoleh ke belakang. “Lelet!” teriaknya gemas.
“Tunggu! Kamunya aja yang kecepetan!” Menunggu sudah jadi makanan Raras setiap saat.
Mereka sampai di warung Mang Odeng, pemilik warung kecil di seberang gerbang sekolah. Sepulang sekolah mereka sering mampir ke sini, sekedar untuk membeli es teh atau mi instan. “Mang, es teh dua.” Raras membuka jaket merahnya. Udara sore itu bukan main, sangat panas. Raras lupa kapan terakhir kali hujan, yang pasti sudah berbulan-bulan tidak turun. Padahal sekarang sudah bulan September. Kata mendiang neneknya, semua bulan yang berakhiran ber adalah bulan penghujan, tapi nyatanya tidak. Ia mengambil karet kunciran hitam di saku tasnya dan menguncir rambut cokelat panjangnya yang terurai hingga sebahu. Merapihkan sedikit anak rambut di dahi dan jidat yang menempel lekat akibat keringat.
“Gimana?” Lita sibuk merapikan jilbab putih yang terlepas bagian bawahnya. Ia sematkan jarum pentul ke bagian bahu dan membiarkan sisa kain putih panjang itu terjulur hingga menutupi tangan. Raras risih ingin bertanya, apa nggak gerah? Tapi lagi-lagi urung. Jawabannya selalu sama, “Aku masih bisa tahan panas matahari Ras, daripada panas api di neraka nanti.” Lebih baik tidak usah ditanya, daripada Raras kena ceramah.
“Gimana apanya? Kan kamu tau aku nggak bisa.” Raras menjawab santai sembari menyesap es teh manis.
“Kan di kafe Ras, bukan di rumah kamu. Bilang aja mau main sama temen atau apa gitu.”
“Kamu ngajarin aku bohong? Nggak takut api neraka?” Lita terdiam jengkel. “Memang mau belajar apa?” Raras kembali bertanya, kali ini dengan serius.
“Stoikio, aku masih belum paham.”
“Katanya mau masuk jurusan kimia, masa stoikiometri belum paham?” Bukan maksud Raras merendahkan Lita. Masalahnya, sudah tidak terhitung berapa kali dia mengajarkan Lita materi yang sama dan Lita masih belum paham juga!
“Justru itu. Ajarin ya, plisss…” Raras tahu sahabatnya itu manis, wajahnya bulat dan berkulit putih dengan mata sipit khas oriental. Dibalut kerudung panjang berwarna putih, mengingatkan dia akan makanan khas Jepang, mochi. Raras masih suka mempertanyakan, bagaimana bisa wajah macam Lita itu muslim, sekeluarga mondok lagi. Orang tuanya hijrah dari Cina ke Arab atau bagaimana? Pakai perahu menelusuri Gurun Gobi begitu? Atau jangan-jangan dia keturunannya Jenghis Khan? Raras bingung.
“Ras! Malah bengong! Gimana?” Lita menyadarkan lamunan Raras yang sudah kelewatan kemana-mana.
Raras menyelesaikan tegukan terakhir es teh manis lalu memakan sisa es batu di dalam gelas. “Tetap aja nggak bisa, Lit. Aku disuruh papa ke tempat mamah.”
“Masih lanjut? Bukannya katanya udah‒”
“Mas Raga tantrum lagi. Aku harus ke sana besok.” Kali ini Lita benar-benar diam bukan karena kesal. “Nih kitabmu. Aku pulang duluan ya.” Raras berjalan ke samping jalan, menghentikan angkot lalu naik mobil bercat biru itu untuk pulang.
-Bersambung-
Popular Posts
Sistem Informasi : "Jangan samakan aku dengan sub-sistem!!"
- Get link
- X
- Other Apps
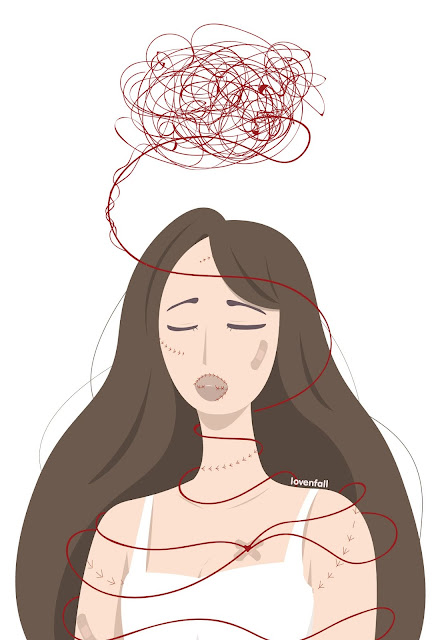

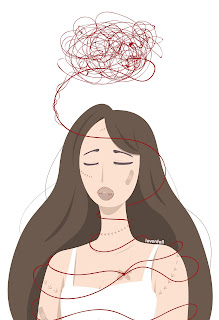
Comments
Post a Comment